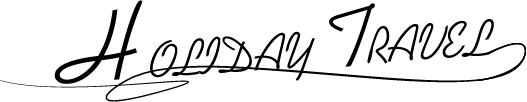
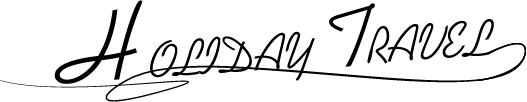
Untuk pertama kalinya hari itu, Aku berdiri tak bergerak, mengamati hamparan putih tak berujung di depan. Baru-baru ini turun salju, dan bedak, semua tapi mengkristal sekarang, telah menyembunyikan jejak kaki yang kuharap akan membimbing kita. Bukit es berkilauan bergelombang seperti ombak, silaunya begitu terang hingga hampir menyilaukan. Itu sekaligus tempat paling indah dan sunyi yang pernah saya kunjungi – hutan belantara batu dan es yang membeku.
“Ada apa?” panggil Mim dari belakangku. Suaranya bergema dan kemudian menghilang, seolah-olah menelan tenggorokan lidah glasial besar yang terjulur di depan kami.
Udaranya tenang tapi tipis. Saat aku menarik napas, dinginnya yang pahit menyengat lubang hidungku. Aku mendengarkan saat es itu berderit dan mengerang. Kami telah disarankan untuk tiba di tahap pass ini lebih awal. Sangat terlambat, wanita tua keriput di pondok telah memperingatkan kami, dan matahari dapat mencairkan gletser, membuka celah yang bisa menghancurkan pergelangan kaki, jika tidak melahap Anda sepenuhnya.
'Ada apa?' Mim bertanya lagi, suara terengah-engah saat dia beringsut di sampingku. Dia menarik bandana biru dari mulutnya. Wajahnya memerah dan terbakar angin, bibirnya pecah-pecah parah.
'Tidak ada.' Saya melindungi mata saya saat matahari memuncaki gunung terdekat, sebuah 7, Puncak 000m menyerupai pisau dapur bergerigi. Aku melirik jam tanganku dengan gelisah. Kami terlambat lebih dari satu jam dari jadwal, dan es sudah mulai menangis.
Enam jam sebelumnya, kami telah terbangun, menggigil kedinginan, di kota sepi Dzongla di timur laut Nepal. Kami pertama kali berangkat dua minggu sebelumnya. Perjalanan kami telah melihat kami mendaki melalui beberapa lingkungan yang paling tak kenal ampun di dunia, menyaksikan vegetasi menipis dan menghilang sepenuhnya saat kami mendaki ke ketinggian yang lebih tinggi dan lebih tinggi.
Kami menyelinap dari kantong tidur kami dan berpakaian dalam diam – kaus kaki wol, kemeja termal, jumper, jaket bawah – sebelum tersandung di lorong gelap menuju ruangan yang bersinar dengan cahaya oranye kusam. Di dalam udara terasa hangat dan berasap. Keheningan itu hanya terganggu oleh derak api yak-kotoran yang menyala di tungku yang tertutup jelaga, dan sesekali berderak saat angin mengguncang pintu.
‘Cho La hari ini, ' seorang pria berkata ketika dia muncul dari dapur, dan letakkan dua mangkok muesli dan mug berisi susu mengepul di depan kami. Aku mengangguk, tidak yakin apakah itu pertanyaan.
“Apakah sulit?” tanya Mim. Pria itu memasang wajah. 'Tidak, ' dia memutuskan setelah beberapa saat. "Kamu pergi sendiri?"
Mim mengangguk. 'Tidak ada porter?' Satu anggukan lagi.
Pria itu tampaknya sejenak mempertimbangkan kembali penilaiannya, tapi kemudian mengangkat bahu. 'Kamu akan baik-baik saja.'
Satu jam kemudian kami berjalan dengan susah payah di sepanjang jalan setapak di ladang berangin, rona merah muda dari matahari terbit di pagi hari yang membingkai tepi Himalaya. Meskipun dingin – termometer membaca beberapa tingkat di bawah nol – kami telah melepaskan jaket dan sarung tangan kami, dan kami berdebat untuk istirahat lagi untuk melepas sweter kami, ketika tiba-tiba Mim berhenti di tengah kalimat dan menunjuk. Di sana, melintasi dataran berbatu, siluet gelap menjulang di kejauhan. Saat kami semakin dekat, garis-garis bergerigi mulai menajam sampai kami mendapati diri kami berdiri di bawah bayang-bayang tebing curam batu hitam.


'Biarkan aku pergi dulu, ' kata Mim. Tanpa menunggu jawaban, dia mengencangkan ranselnya di pinggangnya, melemparkan tongkatnya ke langkan terdekat, dan mulai berebut. Saya melihat kakinya dengan ahli menemukan celah dan pegangan yang bahkan tidak bisa saya lihat. Seperti balerina di atas panggung, setiap gerakan tepat namun lancar, seluruh tubuhnya bergerak sebagai satu.
Saya kurang anggun. Pada saat saya membuang beban berat ransel saya dan menarik diri saya melewati bibir pendakian, Saya ditutupi lapisan tipis keringat. Kami telah mencapai permukaan semi-datar, pelana yang mengangkangi lembah di satu sisi, Cho La di sisi lain. Diantara, puncaknya seperti serangkaian rol yang membeku di tengah istirahat, gletser berkilau seperti sirene di bawah sinar matahari tengah hari.
Saat aku menatapnya, cerita yang telah saya buang dari pikiran saya mulai merayap kembali. Saya ingat kisah-kisah tentang runtuhan dan longsoran batu, batu-batu besar yang jatuh dari tebing di dekatnya dan nyaris tidak ada pejalan kaki. Cuaca, sudah tidak menentu di Khumbu, dikatakan sangat berubah-ubah di sini. Awan yang tampak lembut dan kapas di kejauhan bisa berubah dalam sekejap, menangkap trekker yang tidak curiga dalam badai angin dan salju yang mengancam jiwa.
Menyeberang itu lambat. Gletser yang terkenal tidak stabil diadu oleh celah-celah dan jernih, kolam berkilauan yang sering membutuhkan jalan memutar yang berkelok-kelok, menghabiskan waktu kita yang berharga. Kami tidak punya crampon atau kapak, hanya sepatu bot usang yang seharusnya sudah lama diganti dan tiga tiang berjalan di antara kami. Sebelum mengambil langkah, Saya akan menyodok es dengan cemas, perasaan untuk salju longgar yang akan menandai jurang. Tetap, Saya berhasil memutar tiang saya menjadi simpul saat jatuh ke jurang tersembunyi.
Saraf kami tegang pada saat kami berhasil menyeberang. Di sisi jauh gletser, dan setelah mendaki tebing curam lainnya, jemuran bendera doa yang dikibaskan angin mengumumkan bahwa kami telah mencapai titik tertinggi Cho La Pass. Pukul 5, 420m, kami lebih tinggi dari sebelumnya. Lebih tinggi dari Grand Teton dan Gunung Whitney. Lebih tinggi dari Matterhorn. Tetapi kegembiraan apa pun yang kami rasakan tidak berlangsung lama. Saat saya bersandar di tepi celah, Aku bisa melihat bekas luka switchback meliuk-liuk menuruni lereng scree yang memusingkan.
'Kotoran, ' gumamku. mim, yang telah menatap beberapa sosok seperti semut yang sedang bernegosiasi dengan gletser di belakang kami, berbalik. 'Kotoran, ' dia setuju.
Turunnya sepertinya tidak ada habisnya. Setiap switchback dibuka ke yang baru, setiap tetes yang lebih besar. Dasarnya – ditandai dengan lengan hitam sungai yang bengkok – sepertinya tidak pernah mendekat. Saat kami tersandung dan meluncur turun, tidak pernah membuatnya lebih dari beberapa langkah sebelum batu-batu itu tergelincir di bawah kami, Saya mulai berjuang. Ketakutan, adrenalin, dan konsentrasi yang mematikan pikiran yang diperlukan untuk menuruni lereng curam seperti eskalator mulai menguasai saya.
Kami mencapai pertigaan di jalan setapak. Di kanan, jalan itu berkelok-kelok di tikungan yang longgar. Di kiri, itu membelah jalan setapak, turun dengan cepat dalam beberapa anak tangga batu yang dalam. Mim melirik ke dua arah, dan kemudian berbelok ke kiri. Dia lebih baik dalam hal keturunan, panduan yang lebih baik – lebih baik, dengan baik, semuanya – namun, untuk alasan apa pun, Saya tidak mengikutinya. Aku berbelok ke kanan.


Seperti setelah kecelakaan mobil, Saya tidak yakin persis apa yang terjadi. Itu kabur:dua instan, sebelum dan sesudah. Tapi inilah yang dikatakan Mim terjadi. Mendengar kutukan, dia berputar. Aku menginjak batu, yang pindah, mendorong saya ke depan. Berat badan saya bergeser. Gravitasi ditarik. Lenganku terulur untuk mematahkan kejatuhanku, dan saya ingat merasakan sakit yang tajam saat sebuah batu menusuk tangan saya. Saya mulai berguling – cepat, terlalu cepat – menuju tepi tebing. Kukuku tertancap di tanah dan kakiku menendang tanpa daya saat jurang itu mendekat, lebih dekat…
Dan kemudian saya berhenti, momentum dihentikan oleh batu. Kakiku terpelintir di belakangku, terjebak di bawah berat ransel saya, dan darah menyembur dari tanganku. Aku mendengar langkah kaki, dan kemudian suara panik Mim.
'Tyler! Tyler, kamu tidak apa apa? Yesus, kamu berdarah!’
'Hanya tanganku, ' Saya bilang, menunjukkan padanya. Seperti anak kecil, insting pertamaku adalah menghisap darah dari lukaku, yang sekarang membuatnya tampak seolah-olah saya berdarah dari mulut saya.
“Bisakah kamu berjalan?” Mim melihat ke jalan setapak. Kami hampir setengah jalan, dan benar-benar sendirian. 'Atau aku akan menggendongmu. Atau dapatkan bantuan. Tunggu, tunggu saja di sini.’ Dia mulai berbalik.
'Saya bisa berjalan, ' Saya bilang, tidak tahu apakah itu benar.
meringis, Aku perlahan membuka kakiku dari bawah tubuhku yang kusut. Lutut saya kejang, tapi itu tidak kaku seperti yang saya takutkan. Aku mendorong diriku sendiri. Mim langsung bereaksi, seolah-olah akan menangkapku jika aku jatuh. 'Tidak apa-apa, ' aku meyakinkannya. 'Saya oke.'
Pada saat kami mencapai bagian bawah, saya kaku, kotor, dan berdarah, tetapi sebaliknya tidak terluka. Cedera ringan yang saya derita akan mereda seiring waktu. Begitu juga saraf saya. Selama empat jam berikutnya, kami akan tertatih-tatih menuju pondok terdekat, sering berhenti untuk beristirahat – dan, sekali, untuk memecahkan es yang membeku di atas sungai untuk mengisi ulang botol air kami. Menjelang malam kami akan tersandung ke dalam pondok, di mana Mim akan membungkus tanganku dengan perban sementara dari selotip dan kertas toilet. Dan kami akan makan, dan minum teh, dan hari yang merupakan salah satu hari yang paling menggembirakan dalam hidup saya perlahan-lahan akan memudar dari sekarang hingga saat itu. Itu akan menjadi sebuah cerita. Suatu hal yang harus diceritakan. Sebuah memori, yang entah bagaimana, entah kenapa, tumbuh lebih jelas dari waktu ke waktu.
 Mencari pizza terbaik di New York City
Mencari pizza terbaik di New York City
 Di Sisi Timur Manhattan, sebuah Hotel untuk Pialang Kekuasaan dan Calon Penduduk New York yang Mewah
Di Sisi Timur Manhattan, sebuah Hotel untuk Pialang Kekuasaan dan Calon Penduduk New York yang Mewah
 Microtel Inn &Suites oleh Wyndham Perry
Microtel Inn &Suites oleh Wyndham Perry
 Belanja Perlengkapan Penggemar ASU
Belanja Perlengkapan Penggemar ASU
 Bar yang akan membuat Anda terpesona
Bar yang akan membuat Anda terpesona
 e Petualang dan Bersedia Gagal:'Lebih Baik Panggil Saul' Patrick Fabian
e Petualang dan Bersedia Gagal:'Lebih Baik Panggil Saul' Patrick Fabian

Setiap langkah menghilangkan bagian terakhir dari kekuatanku. Untuk menggerakkan kaki saya perlu berteriak dan meremas semua yang tersisa dalam diri saya. Lagipula tidak ada yang mendengarkan. Jeritan mati dengan cepat di rawa-rawa. Tubuh kita tenggelam lebih dalam ke dalam campuran air cokelat, lumut, dan rumput busuk. Beberapa burung nasar melingkar di atas kami pada suhu panas terakhir hari itu. Kami jauh ke selatan dan hari-hari musim panas panjang di garis lintang ini, tapi malam akan datan

Di ibu kota Jackson, ada komunitas seni publik yang dinamis yang menyambut semua orang yang berkeliaran di Kota dengan Jiwa. lukisan dinding ini, terletak di jantung pusat kota Jackson di sudut jalan Pearl dan State, adalah salah satu yang pertama yang akan dilihat pengunjung datang ke kota dari I-55. Lebih jauh ke kota, di dalam Distrik Bersejarah Farish Street, adalah peringatan untuk Richard Wright yang menampilkan haiku yang ditulis oleh Wright, serta kemiripan yang luar biasa dari penuli

Tujuh hari. Sudah tujuh hari sejak hari pertama. Saya berada di lantai 5 Hodelpa Gran Almirante , menyeruput segelas sampanye di ruang VIP. Aku tampak sedih tidak pada tempatnya, sepatu kotor saya masih basah setelah arung jeram sehari sebelumnya. Aku hanya bisa tersenyum…inilah hidupku akhir-akhir ini. Beda kacau, satu hari ke hari berikutnya. Suatu malam saya tertidur di sebuah resor bintang lima, dikelilingi oleh enam bantal bawah. Malam berikutnya saya mendirikan tenda, atau tertidur di be